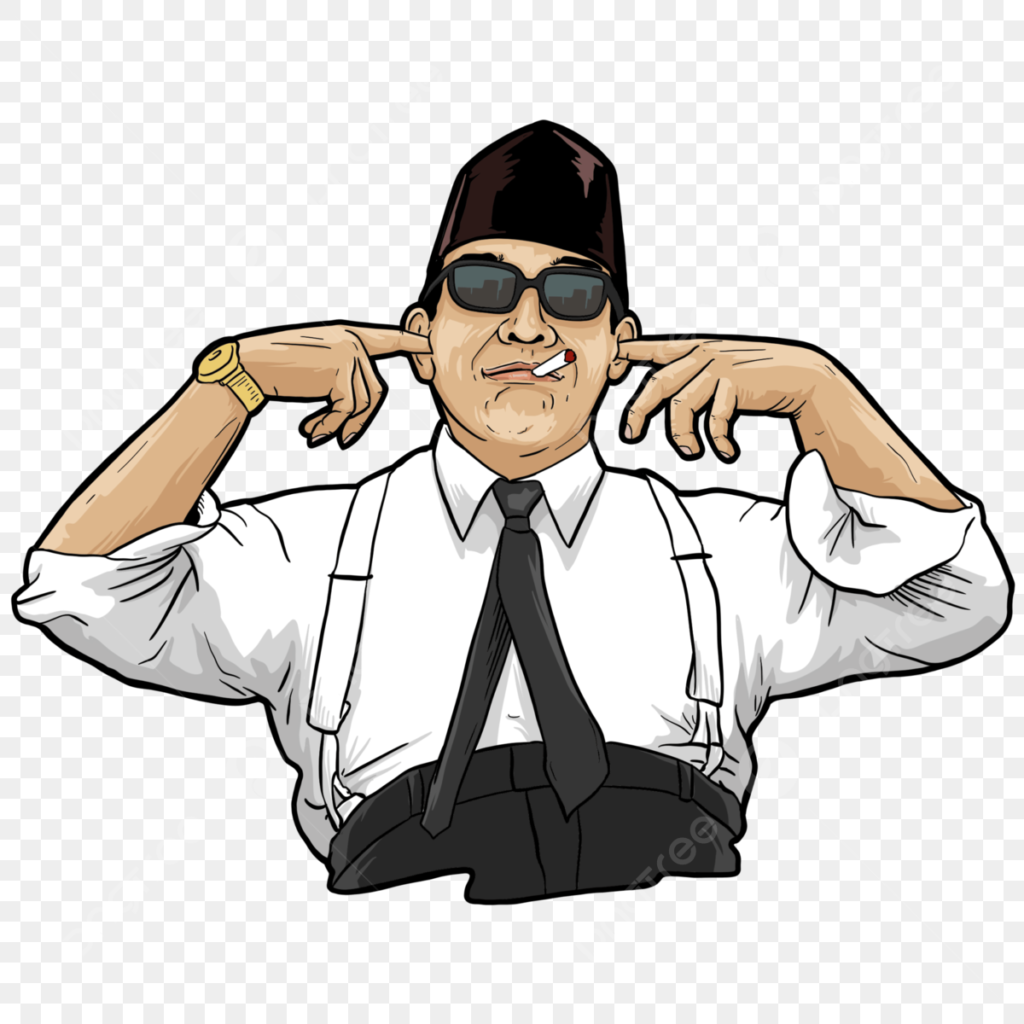
Soekarno adalah catatan sejarah yang penting. Dia adalah arsitek sekaligus kurator yang wajib dibaca. Dialah pembuka bab awal dan akhir kemerdekaan yang harus menjadi mata air keteladanan. Dengan tegas dan kerendahan hati, dia meminta maaf ketika mulai membacakan pidatonya dihadapan peserta sidang BPUPKI di Jakarta pada 1 Juni 1945.
“Saja minta, saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo dan saudara – saudara Islam lain: maafkanlah saja memakai perkataan “kebangsaan” ini, kata Bung Karno memulai pidatonya. “Saja menghendaki satu nationale staat, seperti jang saja katakan dalam rapat di Taman Raden Saleh beberapa hari yang lalu”.
Apa yang dimaksud nationale staat oleh Bung Karno bukan dalam arti sempit, namun dalam arti luas. Dalam teks asli pidato Lahirnya Pancasila, Bapak Proklamasi ini dengan tegas menyuarakan idenya tentang sebuah negara bahwa syarat paling utama lahirnya sebuah negara adalah kehendak untuk bersatu. Ernest Renan menyebutnya sebagai the desire to live together and continue the shared legacy.
Prinsip Demokratis menjadi ciri ide Negara yang diimajinasikan Soekarno. Dia secara tegas menolah sistem monarki yang menjadikan seorang kepala negara bisa mewariskan tampuk kepemimpinan kepada anak atau keluarganya. ‘’Tidakkah agama Islam mengatakan bahwa kepala-kepala Negara, baik kalif, maupun Amirul mu’minin, harus dipilih oleh rakjat?” Realitas yang dihadapi Seekarno pada waktu itu adalah realitas pendudukan Japang dengan fasismenya. Namun, dengan berani dan tak punya celah, penulis Di Bawah Bendera Revolusi ini tegas memproklamirkan kata ‘Demokrasi’. Disana ada kebersamaan, mufakat, dan gotong royong. Disana, ada suara rakyat yang jadi kekuatan.
Namun, apa jadinya jika suara (wakil) rakyat justru memunculkan gesekan dan konflik itu sendiri? Alih-alih menyuarakan protes, mereka sibuk debat kusir, masalah-masalah sosial dan kesejahteraan hanya jadi candaan.
Pancasila dan Masa Depan yang Sunyi?
Yuval Noah Harari percaya bahwa sapiens menaklukkan dunia bukan karena tubuh mereka kuat, melainkan karena manusia punya imajinasi kolektif. Pancasila, pada awalnya adalah imajinasi kolektif-fiktif yang kemudian bertransformasi menjadi kenyataan yang dipercaya dan jadi pedoman bangsa Indonesia. Pancasila lahir dari latar historis berupa kecemasan, harapan dan kebutuhan akan persatuan. Sebagai sebuah ideology, pancasila lahir dan tumbuh – dalam istilah Goenawan – dengan harapan yang tipis dan darah yang terlampau banyak.
Dunia berubah. Indonesia dan dibelahan bumi manapun, sedang mengalami dan menghadapi abad disrupsi yang membuat keyakinan kian kabur, persatuan goyah, dan identitas tak tentu arah. Pancasila harus hadir bukan sebagai kata sakral nan suci, pancasila harus bisa jadi laku tindakan yang lebih objektif dalam keseharian masyarakat Indonesia. Pancasila harus senantiasa jadi pertanyaan-pertanyaan, melahirkan jalan interpretasi yang memungkinkan masyarakat percaya dan punya pegangan. Dengan demikian, harapan itu tetap hadir, meskipun pelan dan kadang sunyi.
Pancasila dan Keseharian
Lima prinsip dalam diktum Pancasila mungkin penting ketika kelimanya hadir dalam sebuah forum kenegaraan. Disana, prinsip itu hampir jadi kata sakral seperti kitab suci. Namun, setelah itu, dia jadi imajinasi kolektif yang dilupakan – tak lagi dipercaya.
Pancasila harus senantiasi hadir dan dihadirkan. Dia harus membumi. Sesuatu yang membumi dengan demikian hadir dalam rupa sosiologis, dengan demikin, punya konteks. Dalam kemajuan Artificial, misalnya, yang semakin mengambil hampir semua ruang kemanusiaan, Pancasila harus jadi laku keseharian. Ketuhanan yang maha esa harus hadir dalam obrolan, apakah relevan atau tidak dalam menjawab persoalan-persoalan pelik abad revolusi teknologis. Kemanusiaan hingga keadilan harus jadi terma, pertanyaan, pembelaan, ataupun perlawanan pada masyarakat yang tertindas, orang-orang lemah dan komunitas yang termarjinalkan.
Pancasila, dengan bahasa keseharian, harus mampu hadir dalam jantung percakapan masyarakat. Kehadiran konsep yang lahir tahun 1945 itu tak lagi harus menegaskan ideology kemerdekaan yang tertutup, namun lebih jauh lagi, harus mampu jadi pegangan hidup kontemplatif dalam mengatasi perubahan zaman yang semakin cepat dan menggerus eksistensi kemanusiaan. Oleh sebab itu, harus ada jarak yang tercipta. Jarak yang memungkinkan kita membaca, mempertanyakan, dan menafsir Pancasila secara terus-menerus. Bukankah dalam sejarah, manusia bisa survive hingga sekarang karena kemampuan mereka untuk terus bercerita dan memproduksi imajinasi kolektif yang dipercaya oleh semua bangsa-bangsa? Wallahu a’lam bishawab!
